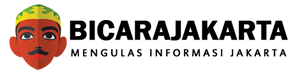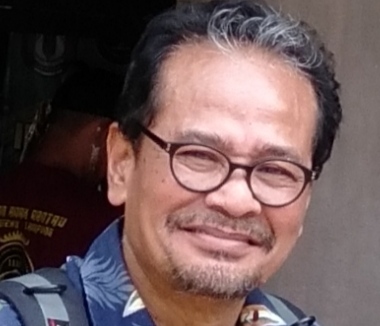Oleh: Suryadi
(Pemerhati Kepolisian dan Budaya)
Polri itu institusi besar dan kompleks. Pendidikan sebagai awal muasal
Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, amat jelas. Rekrutmen dan
pembinaan karir dilakukan dengan konsisten dan konsekuen
terhadap prinsip terbuka berikut segala risikonya, sudah seharusnya
merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan SDM. Dengan
manajemen itu, terjamin’clean n clear’ dari dekil-dekil yang
mengotorinya. Dari situ mau dibawa ke mana Polri, tinggal tergantung
orientasi, menjadi ahli atau raih pangkat dan jabatan. Tegas, agar
terbangun harapan sehingga tak ada apatisme pada anggota. Yang tak habis-
habisnya diperdebatkan adalah, kesejahteraan dulu
profesional kemudian, atau sebaliknya. Apa itu sejahtera?
KEPOLISIAN adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu bunyi UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1.1. Selanjutnya disebutkan, anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah pegawai negeri pada Polri (Ps. 1.2) Dimaksudkan pegawai negeri ada dua, yaitu anggota Polri dan pegawai negeri sipil (PNS) (Ps. 20 (1) a, b).
Selanjutnya, UU tersebut mengatur, setiap anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggungjawab dalam penugasannya (Ps. 25 (1). Mereka memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak (Ps. 26 (1), yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (Ps. 26 2).
Pada 8 Januari 2002 UU ini diundangkan. Polri pun menjadi polisi sipil. Ini buah perjuangan perlawanan ‘alot’ para pegiat hak asasi kemanusiaan (HAM) terhadap penguasa otoriter nan represif. Berjuang bak ungkapan Latin, “Frangas non flectes! –Engkau dapat menindasku, tapi tidak mengubah pendirianku!” (Marwoto ed. al. 2006: 94). Kemudian, Soeharto, pemimpin rezim Orba menyatakan diri berhenti pada Mei 1998. Selamat tinggal Polri masa lalu!.
Rupanya sudah alami, UU datang kemudian setelah segala sesuatu berjalan. Harus ada kejadian lebih dulu. Demikian juga dengan UU Kepolisian yang baru. Tak pelak lagi, harus kerja keras. Problemnya amat dinamis terkadang liar. Harus mengubah kultur manusianya di tengah perubahan politik dari otoritarian ke demokrasi yang labil alias tak kunjung dewasa. Sementara, banyak orang menafsirkan dalam demokrasi kebebasan adalah segala-galanya hingga abai tertib. Mirip-mirip ‘melek’ dulu atau merdeka dulu?. Tentu saja ‘takes time’.
Setelah 19 tahun UU Kepolisian berjalan, saya melihat Polri dihadapkan pada tiga persoalan besar sekaligus: Pertama, belum selesai dengan dirinya sendiri. Kedua, kebebasan yang diametral dengan tuntutan tertib. Ketiga, Polri berpegang pada hukum tidak untuk sekadar menghukum, tapi memberi perlindungan hukum, mulai dari preemtif (sebelum terbangun potensi kriminal), preventif, dan represif. Dalam kalimat lain, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dengan sikap dan perilaku mengayomi dan melayani yang tetap dalam bingkai penegakkan hukum. Butuh energi ekstra dan seni bukan?
Tulisan ini coba memahami persoalan Polri yang “belum selesai dengan dirinya sendiri” berelasi dengan profesionalisme, kelayakan hidup, dan kesejahteraan. Tentu, patut ada komparasi untuk itu. Pastilah, hal ini akan mengundang rasa tidak puas. Apa lagi, bila ‘hidup layak’ dicampuradukkan dengan ‘gaya hidup’ dan ‘biaya kelakuan’, pasti akan menjauh dari sejahtera. Keluhan pun menjadi serupa dengan di masa lalu, tak ada putus-putus sejak ketika masih ‘main otot’ sampai kini sipil
Historikal dan Nilai Juang
TAK terbayangkan bagaimana sebuah negeri dengan Pemerintah dan pemerintahan tanpa polisi. Ketika bumi belahan timur Asia ini masih silih berganti dijajah bangsa asing, polisi sudah ada. Tetapi, kepentingannya tetap yaitu, pengamanan dan penegakan hukum yang berpihak bagi kepentingan kolonial.
Kemudian, tumbuh-kembang Polisi Indonesia beriringan dengan kelahiran Republik Indonesia (RI) dan seterusnya. Serupa dengan laskar-laskar dan badan-badan perjuangan yang lain, Polisi Indonesia basisnya adalah pejuang.
Para perintis polisi Indonesia cuma menunggu momen terakhir untuk ke luar dari Polisi Istimewa Jepang (Tokubetsu Keisatsu Tai). Hanya empat hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, di Surabaya pada 21 Agustus 1945, di bawah kepempimpinan ‘Inspektoer Polisi Kelas I’ Moehammad Jasin, mereka atas nama seluruh warga polisi memproklamasikan (ed. Zachrie dan Wiwanto, 2010: xvii, 1):
“…Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”.
Testimoni salah seorang pelaku peristiwa 10 November 1945,
Surabaya, Jenderal TNI (Purn), Muhammad Wahyu Sudarto menyebut:
“…Jepang yang waktu itu sudah kalah dari Pasukan Sekutu menyerah
kepada RI dan intinya adalah Pak Jasin. Demikian pula Inggris
mendarat di Surabaya. Bila tak ada Pak Jasin, arek-arek Suroboyo
tidak bisa segalak itu”.
Sengaja dikutipkan seperti di atas sebagai nilai juang yang –sudah seharusnya– terwariskan kepada generasi bangsa kini, khususnya semua anggota Polri. Tanggal 21 Agustus 1945 ataukah 1 Juli 1946 yang lebih tepat sebagai Hari Jadi Polri/ Bhayangkara, memang pernah diperdebatkan. Tetapi, biarlah sejarah yang berbicara. Sejarah itu pintu ke luar yang ’care’ tentang hari ini demi masa-masa yang akan datang.
Kini Polri berada di era Reformasi. Perjalanannya pekat ditandai oleh mereka yang telah berjasa pada bangsa dan negara, kemudian berpulang atau pensiun. Generasi terus berganti, jumlah anggota Polri kini sekitar 500 ribu orang. Mereka tersebar mulai dari pusat, Polda-Polda, Polres-Polres, Polsek-Polsek, hingga para Bhintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa-desa. Termasuk di dalamnya sekitar 50.000 anggota Brimob (polisi berkualifikasi tempur skala terbatas).
Polisi-polisi itu dipastikan berusia antara 18 hingga mendekati pensiun 58 tahun, berkarir 0 tahun – 35-an tahun. Menurut ruang kepangkatan, mereka terdiri atas perwira tinggi sekitar 400 orang, perwira menengah mungkin sekitar 1.500 orang (Kombes – Kompol), serta sebagian besar perwira pertama (AKP – Ipda), bintara (Aiptu – Bripda) sampai tamtama (Abriptu – Bharada). Jumlah terbesar para bintara, dengan asumsi setiap Sekolah Polisi Negara (SPN) di Polda-Polda meluluskan rata-rata 200-an Bintara per tahun. Jumlah yang lebih kurang sama diluluskan juga perwira pertama oleh Akpol setiap tahunnya –belum termasuk lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).
SDM dan Yanmas Lini Terdepan
SEJAK dulu hingga kini, bila dirunut dari basis awal pendidikan kepolisian mereka, beragam seturut perubahan nama-nama sekolahnya. Untuk perwira yaitu Akpol, SIPSS, bintara (SPN), dan tamtama (Brimob). Dari masa ke masa, sesuai bertumbuh dan perkembangan jumlah penduduk yang kehidupannya amat dipengaruhi oleh sistem politik dan perekonomian, Polri dilihat oleh masyarakat menggunakan kacamata yang beragam. Sebagai medan juang, kemudian kembali hidup sebagai masyarakat biasa, atau bertahan dengan segala keterbatasan sebagaimana juga dialami oleh para penyandang profesi lainnya di pemerintahan. Ada pula suatu masa, tidak banyak orang mau jadi anggota Polri karena alasan buruknya kesejahteraan.
Reformasi membawa perubahan besar seiring dengan tuntutan demokrasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Polri harus dilihat sebagai profesi berintegritas, bukan sekadar lapangan kerja. Tetapi, sebaik apa pun sistem dibangun, kuncinya adalah SDM yang unggul. Luar biasa, dalam 20 tahun terakhir tumbuh subur polisi-polisi intelektual. Lima – enam tahun muncul ‘gerakan besar’ menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) yang dicanangkan oleh Jenderal Pol. (Purn) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D di awal-awal ia menjadi Kapolri ke-24 pada 2016. Tapi, ia juga memberi catatan, secara organisasi atau struktural, mewujudkan Polri yang Promoter tidak akan sesulit kerja-kerja besar ketika mengubah kultur umum lama Polri (baca: main kuasa, mengedepankan kekerasan, dan koruptif).
Ketika Tito menjadi Mendagri, segera pelanjutnya, Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si (2019 – 2021) mengukuhkan Promoter, seraya ia juga melakukan pemantapan manajemen media (baca: erat berkait dengan membangun dan memelihara imej). Akhir Januari 2021 pensiun, Idham digantikan oleh Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui oleh DPR. Tanpa analisa dan evaluasi (anev) detil terhadap Promoter secara luas terpublikasi, Sigit di hadapan DPR RI menggulir programnya dalam kemasan bernama ‘Presisi‘.
Tentu butuh anev komprehensif terhadap ‘Presisi’ yang sinambung dengan Promoter. Tetapi, ada yang menarik dari paparan Sigit di hadapan DPR (Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Rabu, 20/1/22). Polsek-Polsek tertentu tidak lagi dibebani tugas penyidikan, sehingga berbasis pada resolusi yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Jadi fungsinya, lebih dititikberatkan pada tugas preemtif, preventif, selain penyelesaian-penyelesaian masalah dengan ‘restorative justice’.
Berelasi dengan ‘restorative justice,’ hal itu dinilai bagus oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Maromy. Langkah ini, menurutnya, merupakan kebijakan untuk terwujudnya keadilan dengan mengalihkan ke posisi seperti tidak pernah terjadi. “LP itu bukan satu-satunya tujuan pemidanaan. Banyak kasus justru terpidana yang masuk LP, sekeluarnya malah lebih mahir lagi melakukan kejahatan,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL), Syaefurahman Al-Banjary, S.H., M.Si (Suryadi & Helsi, 2020: 195, 194). Tapi, jika pelakunya memang sudah menjadi profesi, kambuhan, narkoba, pencabulan anak, terorisme, atau kejahatan yang membahayakan masyarakat, tentu tidak pantas masuk dalam pertimbangan penyelesaian ‘restorative justice’.
Dalam pandangan penulis, hal tersebut, juga akan berkait dengan azas manfaat yang harus tetap berada dalam bingkai penegakan hukum. Memang, tidak semua harus masuk ke pengadilan dan berlanjut hidup di lembaga pemasyarakatan (LP). Misalnya, perkara pencurian oleh orang yang bukan memang profesinya. Juga, kasus-kasus yang melibatkan remaja yang bisa dilihat sebagai kenakalan. Sebaliknya, ini sekaligus juga sebagai ‘warning’ bagi Polri, karena amat berelasi dengan mentalitas aparat yang suka memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Maka, profesional adalah integritas dan moralitas yang disertai pengawasan tanpa kompromi.
Satu hal yang mungkin sudah lama disadari, namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu membangun sinergitas internal “jangan hanya ada dalam kalimat’. Maknanya, bahwa semua fungsi sama pentingnya. Tidaklah satu fungsi lebih penting daripada fungsi yang lain, apalagi saling menihilkan. Iklim serupa ini akan menciptakan kompetisi dalam arti bertanding bukan “sikut menyikut bersaing” sehingga terbuka kesempatan bagi semua untuk berprestasi dalam karir. Tanpa melahirkan iklim kerja dengan ‘pendekatan-pendekatan konkret’ pada terwujudnya harapan, yang akan muncul adalah sebuah sandiwara kalau bukan lebih buruk lagi, apatisme.
Penting untuk diluruskan adalah orientasi. Mau jadi ‘polisi karir – polisi ahli’ (PKPA) atau raih pangkat dan jabatan. Jika PKPA, setiap polisi akan cenderung dipacu berprestasi sebaik-baiknya, karena persoalan-persoalan yang sering salah kaprah disebut sebagai ‘kesejahteraan’ sudah konsisten mengikuti fluktuasi prestasi. Kesejahteraan (‘welfare), tulis Setiyono, secara umum mengacu pada ‘well being’ atau kehidupan yang lebih baik berkait dengan kenyamanan, kebahagiaan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri dalam menempuh hidup (2018: 32). Ini harus ada bukan hanya pada masyarakat, tapi dalam lingkungan Polri sendiri.
Apresiasi kelembagaan tidak cuma bisa disamakan oleh ‘charity’ dari seorang pemimpin, seperti beragam penghargaan dan hadiah-hadiah termasuk kenaikan pangkat dan mutasi promosi. Semua proporsional, ’ajeg’ dan realistis dinikmati oleh setiap anggota beriringan dengan tegaknya ‘reward and punishment’ sepanjang berkarir. Pada saat yang sama, perubahan besar pada ‘deploy police’ tidak musiman, atau hanya jika terdapat kejadian luar biasa. Semua dinamis beriringan dengan keahlian dan kematangan menggeluti kondisi kesetempatan (lokalitas). Namun, tidak pula ‘local police, local boy’ menjadi harga mati!
Jadi, banyak atau sedikitnya jumlah anggota bukan sekadar dilihat karena pertimbangan pusat atau bukan pusat, tapi pada urgensi persoalan penanganan dan pelayanan. Sampai hari ini, bukan rahasia lagi dan tidak hanya di Polri, aparat di lini terdepan itu dapat dipastikan lebih minim jumlahnya dibandingkan dengan di pusat-pusat kekuasaan (belum lagi bicara kapasitas dan kualitas). Perlu penataan proporsional menghadapi dinamika persoalan dan konsistensi keinginan besar menjadi pelayan ketimbang penghardik.
Polri kini sudah di zaman yang didukung oleh Iptek. Memang, Iptek bukan segala-galanya, tapi sudah seharusnya mampu menengahi kalkulasi rasio yang sekadar berbasis jumlah polisi berbanding penduduk. ***