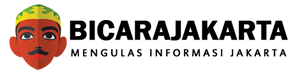Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM.
Kepala LPPM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta/ Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)
Kebebasan mengungkapkan berbagai keinginan dan perasaan yang diungkapkan di media sosial (medsos), kini sudah sangat maju bahkan berada pada titik yang cukup eksplosif.
Ketika berbagai kelompok masyarakat apapun dan dari manapun serta dalam strata apapun, mereka dapat menuangkan dengan mudah apa saja yang dipikirkan dan dirasakan dengan menggunakan medsos.
Sayangnya, hal tersebut tidak bertumbuh secara bersamaan dengan kedewasaan dalam mengendalikan hasrat yang memang fundamental dalam perspektif demokrasi.
Dalam kehidupan ini, baik sebagai pribadi maupun warga negara sebuah bangsa, meski setiap orang mempunyai ‘hak’, patut diingat juga sekaligus memikul tanggung jawab sosial untuk diri dan dunia tempat dia berada.
Maka, upaya terbaik untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam konteks kehidupan peradaban, berbangsa dan bernegara, menempatkan “Kebebasan Berpikir” dengan “Kebebasan Berekspresi” sesuai sebagaimana mestinya adalah keharusan. Inilah pertanda orang cerdas dan berpikir.
Akan tetapi, pada banyaknya kasus pelanggaran terhadap UU ITE No.11 Tahun 2008 yang menerpa berbagai kelompok masyarakat dan bahkan ‘tokoh masyarakat’, tergambarkan sejatinya masih banyak orang dan kelompok dari berbagai kalangan masyarakat kita, belum dapat secara jernih membedakan, antara “Kebebasan Berpikir” dengan “Kebebasan Berekspresi”.
Kebebasan Berpikir
Sebagai manusia, untuk dapat bertumbuh dalam mengembangkan pemikiran genuine dan kreatif membutuhkan “Kebebasan Berpikir” tanpa kekuatiran batasan yang terlampaui.
Memang hakikatnya berpikir adalah ranah kebebasan personal yang hakiki, yang melekat dalan eksistensi setiap orang, yang banyak dianut para filsuf yang beraliran “Eksistensialisme” yang menempatkan manusia pada titik sentrum dalam berbagai relasional kehidupan. Bahkan, Jean-Paul Sartre, filsuf Perancis menempatkan eksistensi di atas esensi.
Persoalan saat ini, ketika ada yang menuangkan opini di media sosial terkena pelanggaran UU ITE, lalu aparatus hukum berkerja sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku (terlepas dari perdebatan kualitas aturan hukum tsb), muncul penolakan terhadap tindakan hukum tersebut yang dengan lantang meneriakkan bahwa telah terjadi upaya kebiri proses demokrasi dengan mengkriminalkan suara-suara kritis.
Celakanya, respons tersebut kemudian dibenarkan dan direspon pula dengan emosional dari kelompok lainnya, tanpa mengkritisi dan mencari tahu lebih detail substansi permasalahannya.
Wajar saja, maka yang muncul lebih besar lagi malah eforia kontra produktif yang cukup menyita energi anak negeri terjadi.
Idealnya, sebagai ungkapan yang terlahir dari rahim pemikiran, buah pikiran adalah upaya kontribusi gagasan dari kecerdasan. Bukan emosi tanpa landasan.
Keinginan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam kesertaan membangun peradaban kehidupan manusia dan kemanusiaan, sebenarnya, adalah alasan utama dari tindakan berpikir yang dilakukan. Sehingga, kebermanfaatan diri berkontribusi positif dapat terjadi.
Kebebasan Berekspresi
Dalam Universal ‘Declaration of Human Rights’ utamanya di pasal 19 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui apapun dan tanpa memandang batas negara”.
Merujuk ketentuan itulah, kini yang banyak digunakan sebagai landasan universal kebebasan dimaksud hingga melampaui proporsinya.
Jika untuk ketentuan nasional, kita dapat merujuk kepada UUD 1945 tentang kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Bahkan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, berkata bahwa: “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang.
Berdasarkan rujukan hukum dan filosofis di atas, pertanyaan yang muncul adalah, apakah setiap orang dapat bebas tanpa batas dalam mengekspresikan apa yang terpikirkan?. Lanjutannya, apakah jika ada yang membatasi apapun alasannya, itu dapat dikatagorikan mengkebiri Demokrasi ?.
Perlu kita melihat dan menganalisa, bahwa saat ini jagat media sosial kita banyak diwarnai oleh pernyataan oleh orang yang hanya sekadar menuangkan gagasannya di media sosial, para tokoh yang semangat menyebarkan informasi dari perspektif demagogi yang didominasi semangat mencari sensasi dalam arus psikologi massa.
Ketika sebuah isue yang dihembuskan dan dikemas dengan narasi menarik, di tengah arus massa yang belum terlepas sepenuhnya dari sindrom ‘Melodramatik”, yaitu sebuah situasi di mana massa memiliki daya ingat yang relatif singkat, yang ditandai dengan sikap cepat marah, cepat sedih, cepat gembira, cepat kasihan dalam merespon sebuah peristiwa, tanpa mau bersusah payah mencari tahu (tabayun), akan substansi masalah sebenarnya, menjadikan para pengusung “Demagogi” tadi menemukan ladang pengikutnya.
Hal seperti itu tidak membantu mendorong kecerdasan dalam menebar informasi buat khalayak, bahkan ikut membebani dan menahan laju kemajuan pola pikir anak bangsa dalam merespon perkembangan peradaban.
Benar adanya ketika “Kebebasan Berpikir” harus tanpa batas dalam mengekplorasi berbagai keingintahuan manusia. Tetapi, ketika buah pikiran itu mau dan akan diekspresikan, tentu ada batasan yang harus dijadikan pertimbangan, baik itu batasan norma, adat, budaya, etika, moral dan hukum yang berlaku dimasyarakat atau di sebuah negara.
Oleh karena itu, manakala sesuatu buah pikiran dan gagasan yang diekspresikan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan batasan-batasan normatif dan hukum yang berlaku, maka dengan sendirinya dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara ada rambu yang dilanggar yang berkonsekuensi beragam, dari mungkin dapat menyebabkan sanksi moral bahkan mungkin sanksi hukum, dan ini tentu saja sebuah bentuk logika kausalitas dalam kehidupan sosial, bahwa kita tidak hidup sendirian di bumi peradaban.
Hakekat sebenarnya, bahwa di ujung kebebasan seseorang ada hak orang lain yang juga harus dihormati, karena kalau tidak kita akan terjebak pada egoisme monopoli makna kebenaran dengan menegasikan hak orang lain itu tadi. Saya tertarik dengan ucapan yang pernah diungkapkan oleh mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang mengatakan bahwa “Aku belum benar-benar bebas jika aku mengambil kebebasan orang lain”.
Untuk itulah saya berpendapat bahwa “Kebebasan Berpikir” tidak sama sebangun dengan “Kebebasan Berekspresi”. ***