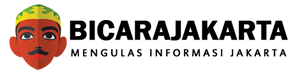2. IMAN SANTOSA HOEGENG
Oleh: Suryadi & Helsi Dinafri
Suryadi, Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)/Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL). Helsi Dinafri, Praktisi Komunikasi

DENGAN sikap dasar sebagaimana warga negara di hadapan hukum (equal before the law), tanpa harus kehilangan rasa hormat pada orang lain dan kehormatan diri sendiri, tentang sosok Hoegeng dapat diikuti dari bagaimana ia ada dalam wujud “satunya kata dengan perbuatan”.
Tak peduli itu kepada Presiden. Terhadap Soeharto, misalnya. Ia begitu saja merespon balik, ”Kalau begitu, saya keluar saja,” ketika “Bapak Presiden” dengan dingin berkata kepadanya, “Di Indonesia tak ada lagi lowongan, Mas Hoegeng.” (Yusra dan Ramadhan, 1993: 369).
Saat itu jelang enam tahun pasca Tragedi Berdarah 30 September 1965. Peristiwa 1965 telah mengantarkan kejatuhan dua dasawarsa Pemerintahan Sukarno (BK), dan pada saat yang sama melejitkan Soeharto ke kursi Pj. Presiden (kemudian Presiden definitif). Dalam peristiwa 1965, telah terjadi pembunuhan keji oleh PKI terhadap enam jenderal petinggi TNI AD, termasuk KSAD Ahmad Yani, dan seorang perwira pertama ajudan Menkohankam/ KASAB, Jenderal A.H. Nasution.
Soeharto saat itu menjadi figur yang sangat populer, baik di kalangan masyarakat maupun jajaran pendukung utamanya, yaitu ABRI, birokrasi pemerintahan, dan Golongan Karya (kemudian populer dengan ABG). Sebab, dengan mudah ia telah berhasil seketika menyimpulkan dan mengungkap bahwa PKI adalah dalang sekaligus pelaku pemberontakan 30 September 1965. Ia juga segera membubarkan PKI, meski klausul itu tak tercantum dalam Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno (BK).
“Surat Sakti” bagi Soeharto tersebut, hingga kini tak diketahui mana yang asli di antara arsip yang resmi tersimpan. Mungkin sebenarnya sudah ada yang tahu, bahwa menurut UU “benda bersejarah” semacam itu wajib diserahkan kepada lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), namun sengaja “digelapkan”, termasuk dengan alasan khawatir akan mengenang perpecahan di antara sesama anak bangsa. Padahal, sesuatu yang di masa lalu rahasia (termasuk hal-hal terkait sejarah politik), tiba pada batas waktunya menurut UU RI No. 43/ 2009 tentang Kearsipan, dapat diungkap kepada publik. Negara-negara maju memberlakukan hal serupa. Bagi Indonesia, hal ini sejalan dengan jiwa Reformasi 1998 untuk memenuhi tuntutan keterbukaan sebagai keniscayaan dalam alam demokrasi. Bukan semata-mata alasan demi kebebasan!.
Berkaitan dengan tindakan amat brutal komunis, sepanjang masa PKI merupakan isu paling emosional di negeri ini. Sangat efektif untuk menggugah sentimen dan kebencian politik mayoritas rakyat Indonesia terhadap hal-hal yang berbau atau tegas-tegas memang komunis dengan mengidentikkannya dengan kekejaman nan brutal dan atheisme.
Oleh karena itu, wajar bila orang-orang seperti Soeharto mendadak mendapat dukungan politik dari masyarakat dan berbagai kalangan, untuk naik ke kursi kekuasaan. Pasca September 1965 namanya baru menaik dan ketika berkuasa, masa lalunya sebagai pejuang banyak digali dan dipublikasikan untuk mengokohkan kepemimpinannya. Seperti sering diperdengarkan dalam tuturan sejarah terkait politik: sejarah menjadi milik penguasa.
Tak cuma sebatas pembubaran PKI yang ia lakukan. Tahun-tahun berikutnya terjadi pembasmian orang-orang PKI atau yang di-PKI-kan, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah, terbesar di Jawa dan Bali. Bung Karno (BK) dikucilkan dari rakyatnya dan diturunkan dari kursi kepresidenan melalui justifikasi konstitusional terhadap penolakan pidato pertanggungjawaban BK di hadapan sidang MPRS. Kalangan ilmuwan melihat hal ini semacam kudeta bertahap dan menyebutnya “kudeta merangkak”.
Selanjutnya, pembersihan dilakukan terhadap para pengikut BK, terutama dalam pemerintahan. Era dan pemerintahan BK disebut rezim Orde Lama (Orla), sementara Soeharto menyebut diri dan eranya sebagai era Pemerintah Orba seraya menggulir pernyataan “koreksi total” terhadap Orla.
Tindakan penyingkiran tersebut, disertai tuduhan bahwa seseorang terlibat atau setidaknya digolongkan sebagai anggota/simpatisan atau anasir PKI. Stigma PKI yang merata-rata kepada WNI sendiri dibarengi oleh “kebijakan” pintu tertutup bagi anak keturunan mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil, militer, dan “wilayah-wilayah lain” yang dinilai sensitif atau patut dianggap bakal menggangu jalannya roda pemerintahan Orba. Intinya, hak perdata mereka dibunuh. Kekritisan pers pun terkait hukum, keadilan, dan hak asasi manusia (HAM) saat itu sangat terbatasi, bila tidak ingin dikatakan nyaris kehilangan daya.
Perlakuan seperti itu berlangsung tiga dasawarsa sampai rezim Orba yang pernah sukses dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7% tumbang pada 1998 menyusul krisis ekonomi yang mengekskalasi menjadi krisis multidimensi dan pada saatnya bermuara pada politik. Meski pada kenyataannya ada saja yang lolos, misalnya, salah seorang jenderal yang menjadi korban 1965 –tentunya meninggalkan istri, anak dan anggota keluarga dekat lainnya– ternyata ia kakak-beradik dengan tokoh PKI. Pada era Orba, yang seperti itu dipadankan dengan “tidak bersih lingkungan” yang biasa dipasangkan dengan “tidak bersih diri” (Lihat, “Kamus Gestok”, 2003: 31 dan Kamus Kejahatan Orba, 2010: 30 – 31)). Stigma memakan tuannya sendiri!
Pendek kata, Soeharto dengan para pendukung utamanya, menonjol dengan ciri otoriter dan karenanya cepat bertindak represif manakala ada sesuatu yang mereka anggap potensial mengganggu kepentingan jalannya kekuasaan Orba dengan jargonnya “Koreksi total”. Untuk itu, tersedia lembaga ekstrajudisial yang militeristik sebagai tangan kekuasaan yang luar biasa efektif. Namanya Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di pusat dan Pelaksana Khusus Daerah (Laksuda) untuk tingkat daerah. Institusi hukum, seperti Kepolisian tunduk padanya.
Dipertuakan?
DALAM situasi dan kondisi seperti itulah, terutama cerita tentang Hoegeng di ujung-ujung puncak karirnya dilanjutkan. Ini cerita Hoegeng di kediaman Soeharto, Jalan Cendana Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah menghadap orang paling berkuasa di masa Orde Baru itu, ketika akan meninggalkan Cendana, Hoegeng mendapat “pertanyaan nakal” dari salah seorang di antara wartawan yang sedari tadi telah menunggu-nunggunya: “….saat ini Pak Hoegeng berusia 49 tahun lebih, jelang 50. Sekarang kami mau tanya. Apakah Bapak sedang diremajakan atau dipertuakan? Sebab, pengganti Bapak lebih tua daripada Bapak?”
Hoegeng yang tak “kemaruk” (makan lahap setelah sangat kurang nafsu makan karena sakit, pen) jabatan terkesan mengalah. Terungkap dari ”HPIK” , ia menjawab wartawan: “Bahwa peremajaan tak usah dilihat dari umur pengganti saya yang lebih tua. Bahwa saya diganti dengan Pak Hasan karena dalam segala hal Pak Hasan lebih progresif.” Kemudian, ketika wartawan menggodanya dengan yel-yel “Pak Hoegeng ngibul, Pak Hoegeng ngibul”, ia pun menutup, “Baiklah kalau Anda menganggap saya ngibul maka wawancara tak perlu dilanjutkan. Jadi sampai di sini saja”. Kemudian ia menaiki jeep dan menyetirnya sendiri pergi meninggalkan wartawan yang meminta, “Jangan, jangan Pak.”
Atas kejadian tersebut, ada semacam perasaan bersalah pada Hoegeng. Ia mengaku merasa terharu. “Seakan saya mengecewakan anak-anak saya sendiri,” aku Hoegeng (Yusra dan Ramadhan, 1993: 372 – 373). Apalagi faktanya, usia Mohammad Hasan memang lebih tua daripada dia, namun lebih junior dilihat dari pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)-nya, yaitu Angkatan V/Wijasa.
Cerita Hoegeng dan wartawan itu, berkaitan langsung dengan kejadian sebelumnya di ruang dalam, yaitu Hoegeng kepada “Bapak Presiden” Soeharto telah dengan tegas menyatakan menolak didubeskan (untuk Belgia). Alasannya, politik bukan bidangnya dan ia tak bisa berdiplomasi. Beda dengan Mohammad Hasan. Selepas menjadi Kapolri ke-6, ia menjadi Duta Besar RI untuk Malaysia (1974 – 1978). Itulah pilihan masing-masing!
Secara resmi sampai saat ini tak ada penjelasan tentang alasan mengapa Hoegeng secepat itu diberhentikan dari jabatan Kapolri. Dia menjadi Kapolri sampai 2 Oktober 1971. Saat itu usianya baru 49 tahun, sedangkan batas usia pensiun perwira ABRI termasuk Polis 55 tahun. Pada praktiknya, dengan alasan dan karena untuk jabatan tinggi tertentu, bisa saja seorang perwira tinggi diperpanjang usia pensiunnya sejauh dikehendaki (oleh “Bapak Presiden”). Jadi teringat Wapres ke-3 Adam Malik yang melontarkan kalimat, “Semua bisa diatur”.
Diketahui, masa jabatan seorang Kapolri dengan Kapolri lainnya, dalam keadaan normal sekalipun tak ada yang sama. Meskipun begitu, Kabag Personalia Hankam, Jenderal Sayidiman dalam keterangan persnya seperti dikutip Tempo (29/9/1971) mengatakan, “Masa jabatan Pak Hoegeng sebagai Kapolri sudah habis, itu prinsip utama, bukan soal umur. Segala sesuatu harus tunduk pada peraturan, bukan seperti zaman Bung Karno dulu” (Yusra dan Ramadhan, 1993 372).**