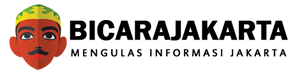5. IMAN SANTOSO HOEGENG
Oleh: Suryadi & Helsi Dinafri
Suryadi, Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)/Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL).
Helsi Dinafri, Praktisi Komunikasi
JANGAN-jangan Soeharto ketika memilih Hoegeng menjadi Kapolri telah salah perkiraan, bahwa laki-laki lugu itu akan dengan mudah menuruti saja kemauan “Bapak Presiden”.
Padahal, Soeharto bukan orang yang baru saja mengenal Hoegeng. Ketika Hoegeng masih Sekretaris Kabinet Inti/ Presidium dengan kedudukan Menteri, Soeharto adalah Wakil Perdana Menteri (Waperdam) bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Inti/ Presidium (17 Maret 1966 – 25 Juli 1966). Presidium ini diketuai J. Leimena (Ready Susanto, 2011: 89 – 90).

Soeharto bahkan sebelum mengangkat Hoegeng menjadi Kapolri, lebih dulu meminta persetujuan yang bersangkutan. Ketika ia bersama calon wakapolri, Tengku Azis, menghadap atas panggilannya, “Bapak Presiden” memberi arahan singkat (briefing) mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dunia kepolisian di Indonesia:
“Saya minta Mas Hoegeng supaya polisi pada tugasnya sebagai polisi.
Jadi, jangan mikir tugas Angkatan lain, yaitu ‘perang-perangan’. Di tubuh
Kepolisian jangan ada lagi grup-grupan di kalangan para perwira, yang
satu sama lain saling tendang (Yusra dan Ramadha, 1993: 300).
Dengan ditariknya Kasus Sum Kuning dari tangan Kepolisian (baca ranah hukum) ke Kopkamtib, berarti “Bapak Presiden” telah berbuat melawan briefing-nya tentang Kepolisian agar berada pada proporsinya. Ia telah menjilat air liur yang telah diludahkannya. Lebih daripada itu, hukum di negara yang berlandaskan hukum sebagaimana konstitusi Negara, menjadi berada di bawah kekuasaan. “Bapak Presiden” telah menjilat air liur yang sudah diludahkannya.
Mungkin “Bapak Presiden” juga sempat lupa, bahwa Hoegeng adalah sosok yang dalam bergaul dengan sesama, tak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Apalagi, cuma atas dasar status sosial. Demikian juga juga dari sudut perbedaan posisi, paham, dan pilihan politik. Jika berhadapan dengan seseorang, Hoegeng akan menghadapinya sebagai manusia biasa (Yusra dan Ramadhan, 1993: 18) sebagaimana dirinya sendiri. Maka, tak ada yang aneh jika Hoegeng berteman baik dengan dr. Subandrio. Mantan Waperdam dan Menlu di era BK (1961 – 1966) ini, sebelum dibebaskan dan meninggal adalah terpidana terkait keterlibatannya dalam Peristiwa G30S 1965.
Hoegeng biasa menyapa akrab Subandrio dengan Mas Ban. Hoegeng berteman baik dengan Mas Ban saat Hoegeng masih mahasiswa RHS (Recht Hoge School/ Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia. Mas Ban waktu itu mahasiswa kedokteran. Bahkan, di masa revolusi Kemerdekaan (akhir 1945), ia sebagai anggota polisi ditugasi mendampingi Mas Ban dan Sayuti Melik yang mendapat tugas dari Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro mempelajari hal-hal yang terkait dengan “Revolusi Sosial” di tiga daerah, Tegal – Berebes – Pemalang.
Rangkaian Peritsiwa Tiga Daerah itu berlatar belakang sosio-ekonomi. Akar sejarahnya sudah ditanamkan sejak lama oleh kolonial. Di masa kolonial kental ditandai tekanan, penindasan, kesengsaraan, dan kemelaratan. Hal serupa ini telah memupuk rasa benci dan dendam masyarakat bukan hanya kepada penjajah, melainkan juga terhadap penguasa-penguasa tradisional yang berpihak kepada penjajah demi status sosial yang membawa kenikmatan hidup mereka sendiri. Dalam peristiwa ini banyak berjatuhan korban (tidak dibahas lebih lanjut).
Keakraban Hoegeng dengan Mas Ban juga tergambar saat pelantikan Hoegeng menjadi Menteri Iuran Negara, Juni 1965. Saat itu, Mas Ban sebagai Menlu sedang berada di Aljazair. Ia menyempatkan diri mengirim telegram. Dengan hangat Mas Ban menyampaikan semacam ucapan selamat. Telegram itu hanya berbunyi, “Diancuk, kowe diangkat pula jadi Menteri.” Bagi Hoegeng, ucapan ini terasa luar biasa manis sehingga begitu membacanya ia tertawa terbahak-bahak. Ini ucapan paling orisinal (Yusra dan Ramadhan, 1993: 17 – 18). Sungguh keakraban dari seorang teman asal Surabaya, Jawa Timur. Suroboyoan!
Gaya Suroboyoan Mas Ban itu mengingatkan Hoegeng pada keakraban gaya Pekalongan yang ia rasakan mirip-mirip. Di Pekalongan Hoegeng lahir dan bertumbuh bersama teman-teman sepermainan sejak kecil sampai lulus HIS (Holandsch Inlandsceh School, kini SD) dan MULO, (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, kini SMP). Selepas MULO ia masuk AMS (Aglemene Middlebare School, sekarang SMA) di Yogyakarta.
Serupa dengan Mas Ban, tapi beda momen, terjadi pula pada Menteri Iuran Negara Hoegeng ketika Hasan (Bongkok). Teman sepermainan semasa HIS di Pekalongan ini, datang menemuinya ketika ia sudah menjadi Menteri Iuran Negara. Teman kecilnya itu ngomong dalam gaya Pekalongan yang bagi orang awam dapat menimbulkan kesan seenaknya. Apalagi ketika itu Hasan menemui Hoegeng yang sudah menjadi Menteri di kantornya (sekarang Kementerian Keuangan).
Begitu pintu dibuka, Hasan masuk ruangan Menteri langsung nyerocos. Seketika Hasan menyemburkan “sumpah serapah” yang membuat suasana jadi berubah hangat dan gembira, “Asu, kowe (anjing, kamu) benar-benar asu ya, gendeng (anjing ya, gila) benar wong (orang) Pekalongan bisa-bisanya jadi menteri!” Hoegeng dan Hasan kemudian larut dalam suasana pertemanan semasa masih di Pekalongan. Mereka bersalaman dan berangkulan sambil mengumbar tawa keras-keras.
Hasan menjumpai Hoegeng hanya untuk kepentingan sebatas itu saja; menunjukkan kegembiraan karena temannya bermain layangan semasa kecil itu, telah menjadi menteri. Tak ada kepentingan lain. Tentang hal serupa itu, Hoegeng mengatakan, “…dalam batok kepala saya, baik dalam gaya Pekalongan atau barangkali juga gaya Surabaya, yang penting adalah rasa akrab yang hangat. Orang Pekalongan dan Surabaya memang unik dalam hal ini…. Hasan agaknya lebih risau berhadapan dengan sekretaris saya daripada dengan saya sendiri yang sudah menjadi Menteri. Sebaliknya, saya sendiri tidak merasa lebih tinggi dari Hasan.… ” (Yusra dan Ramadhan, 1993: 15 – 18). Bandingan dengan kebanykan orang-orang di masa kini. Kekita menjadi pejabat, mendadak berubah jadi bossy da karenanya sulit ditemui.
Sikap Menteri Iuran Negara Hoegeng yang tak berubah itu, diakui oleh sekretarisnya, Soedharto Martopoespito. Di dalam ruang kerja Hoegeng, seperti diungkap dalam ”Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan” (HPMT, Suhartono, 2013), tidak ada dinding sekat pembatas ruang dengan Soedharto dan seorang lagi stafnya. Dengan demikian, mereka tahu apa pun yang dibicarakan dan diperbuat tamu atau yang ditamui. Sejarawan Prof. Asvi Warman Adam menyebutnya sebagai sikap terbuka. Bahkan, Hoegeng tidak takut pada atasan. Namun, itu pula yang menyebabkan ia dicopot dari jabatan Kepala Kepolisian pada 1971 oleh Presiden Soeharto (Santoso dkk., 2009: xvi).
Keterbukaan itu pula yang ditunjukkan oleh Hoegeng ketika setiap sebulan sekali ia rutin menyambangi penjara-penjara, termasuk penjara di Jakarta yang dihuni oleh Mas Ban dan Oemar Dhani. Hoegeng mengungkapkan, “…suatu ketika saya tahu, bahwa bersama Omar Dhani sudah saatnya dr. Subandrio dibebaskan dari penjara. Tetapi, ternyata ketika saya menemui dr. Subandrio, ia tidaklah dibebaskan. Tidak juga Omar Dhani. Dan belum ada tanda-tanda yang jelas kapan mereka akan dibebaskan. Dalam keadaan demikian saya mengunjungi dr. Subandrio di LP Cipinang (Yusra dan Ramadhan, 1993: 21).
Peristiwa Madiun dan G30S
LEBIH daripada sekadar tidak khawatir bakal dipecat “Bapak Presiden”, Kapolri Hogeng rupanya juga tidak takut bakal distigma terindikasi dekat dengan PKI. Sebab, Hoegeng bukan orang yang dadakan menentang komunis. Seberapa pun perannya dalam penumpasan pemberontak PKI di Madiun (1948), Hoegeng yang waktu itu taruna Akademi Polisi (Mertoyudan, Magelang kemudian Yogyakarta) adalah juga polisi aktif. Sebagai anggota polisi, waktu itu ia menjadi staf Soemarto, Wakil Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang memimpin pasukan polisi ke Madiun.
Saat itu, catat Hoegeng, Kepolisian mengerahkan Mobil Brigade (Mobrig, kini Brimob) Jawa Timur dan Jawa Tengah di bawah pimpinan antara lain Joesoef Djajengrana, Koesnadi Soekari, dan Wiroto. Kepolisian juga mengerahkan pasukan di bawah pimpinan para perwira staf, seperti Soetjipto Joedodihardjo dan Soejoed bin Wahjoe (Yusra dan Ramadhan, 1993: 161). Dalam rangkaian usaha merebut kembali Madiun dari PKI (1948), peran Kepolisian khususnya Mobrig tak bisa diabaikan, termasuk peran Bapak Brimob Komjen M. Jasin (Lihat ed. Zachrie dan Wiwanto, ”Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang”, 2010: 130 – 147).
Hoegeng mengaku bukan orang politik. Setidaknya dalam pengertian politik praktis. Saat peristiwa G30S, ia baru menjadi Menteri Iuran Negara. Mengetahui para jenderal yang menjadi korban sebelum dinaikkan ke atas truk, lebih dulu dianiaya dan diseret di hadapan anak dan istri mereka, Hoegeng sedih dan sakit hati.
Saking tak dapat menahan keperihatinan yang mendalam, sampai-sampai dalam suatu sidang Kabinet di Istana Bogor pasca Peristiwa G30S yang dipimpin BK dan dihadiri para menteri termasuk Mas Ban, Menteri Hoegeng angkat bicara: “Sudah pada tempatnya dilakukan pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap para pelaku G30S, untuk selanjutnya menyeret mereka ke forum pengadilan” (Yusra dan Ramadhan, 1993: 281).
Usai sidang Kabinet, Mas Ban melalui ajudannya berpesan agar dari Bogor Hoegeng langsung singgah ke rumahnya. Sore itu juga ia menuju rumah sahabatnya itu di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Setiba di situ, Mas Ban (+) langsung “menyembur” Hoegeng (-) dan memanaslah “perang” Pekalonganan – Suroboyoan:
(+) Mengapa dalam rapat kamu bicara? (mendamprat dan mencela dengan nada
tinggi)
(-) Saya anggap perlu! Emangnya kenapa?
(+) Nanti BK marah sama kamu
(-) Biar marah. Sekalian dipecat juga tidak apa.
Begitulah Hoegeng kalau sudah sampai pada hal prinsip dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dia tak peduli dengan teman dekat sekalipun.
Selang setelah perbantahan yang memanas itu, beberapa saat dia dan Mas Ban terjebak terdiam dan saling pandang. Akan tetapi, tak lama kemudian suasana seketika cair beriringan dengan keluarnya suguhan sepiring besar durian.
Seperti sepakat tak jadi meneruskan marah, mereka berdua pun tenggelam dalam nikmatnya durian yang ketika baru dikeluarkan saja sudah menguarkan aroma tajam dan harum. “Marah sama-sama kami lepaskan pada durian! Jadi, kami hanya bertentangan dalam (soal Hoegeng bicara) di tengah sidang lkabinet (tadi). Dalam perkara durian, memiliki selera dan kegairahan yang sama,” kata Hoegeng (Yusra dan Ramadhan, 1993: 282).**