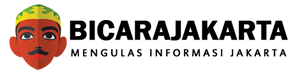7. IMAN SANTOSO HOEGENG
Oleh: Suryadi, Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)/Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL)
Helsi Dinafri, Praktisi Komunikasi
DALAM berkarir di Kepolisian Hoegeng tidak langsung begitu saja menjadi polisi. Lulus AMS Yogya, Hoegeng ke Batavia (kini Jakarta). Pada 1940, di Batavia ia mulai kuliah ke Recht Hoge School (RHS, Sekolah Tinggi Hukum), dengan keinginan kelak masuk Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi.
Hoegeng pengagum sahabat baik Ayahnya, Ating Natadikusumah, Kepala Kepolisian dan Hukum Karesidenan Pekalongan yang jujur, profesional, dan memiliki kepedulian sosial tinggi (Asvi dalam Santoso dkk, 2009: xv). Tentang pilihannya menjadi polisi, Hoegeng mengaku (Yusra dan Ramadhan, 1993: 68):
”Suatu impian sejak kecil yang samar-samar masih hidup dalam diri saya.
Sebab sampai sejauh itu saya belum dapat gambaran apa-apa tentang
kehidupan di kepolisian. Kedua orangtua saya menyerahkan pilihan
Pendidikan pada saya sendiri, meski Eyang Putri (nenek, pen) lebih ingin
saya masuk MOSVIA (Sekolah Pamong Praja, pen) di Magelang saja supaya
nanti jadi ‘kanjeng’ atau pegawai pamong pemerintahan”
Teman-teman mahasiswa seangkatan Hoegeng di RHS, antara lain rekan ngamennya sewaktu bersekolah AMS di Yogya, Totti Soebianto, selain Koyama (orang Jepang), dan Soebadio Sastrosatomo. Totti yang asal Purwokerto juga berkarir di kepolisian, terakhir ia perwira tinggi dengan jabatan Asisten Logistik Polri. Hoegeng dan teman-teman kuliah tak sampai tamat lantaran RHS dibubarkan Jepang yang datang menjajah Hindia Belanda (kini Indonesia) menyusul kekalahan sekutu pimpinan Amerika Serikat (AS). Belanda merupakan bagian dari sekutu.
Sejarah mencatat, fasis Jepang meletuskan perang di Pasifik. Jepang memulai perang dengan pengeboman tiba-tiba terhadap pangkalan terbesar AL AS Pearl Harbour di Pasifik, sebagai usaha membangun imperium di Asia. Melanjutkan penyerbuan ke Hindia Belanda, Jepang masuk dari laut mulai dari timur, di antaranya kota-kota penting dengan kilang-kilang minyaknya di Kalimantan. Saat masuk menyerbu Sumatera, Jepang pun berhasil menguasai Palembang yang juga memiliki kilang minyak.
Pada penyerbuan di Jawa, militer penjajah Belanda tak kuasa menahan serangan Jepang di Jateng dan Jatim. Pada 1 Maret 1942 Tentara Ke-16 Jepang dalam waktu singkat mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu Eretan Wetan (Jabar), Kragan (Jateng), dan di Teluk Banten (dekat dengan Batavia, pen). Dari Banten, Jepang terus menusuk masuk ke Batavia dan Jawa Barat.
Dalam perkembangan terakhir, terungkap dalam “Sejarah Nasional Indonesia VI”, Panglima Angkatan Perang Belanda di Hindia Belanda, Letjen H. Ter Poorten, menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara ekspedisi Jepang pimpinan Letjen Histoshi Imamura, terhitung 8 Maret 1942. Berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda dan dengan resmi ditegakkan kekuataan Kemaharajaan Jepang (Poesponegoro dan Notosesanto, 1993: 1-5).
Perubahan drastis pertama yang Hoegeng hadapi adalah Jepang menutup RHS. Santoso dkk. menulis, setelah menganggur sebulan, akhirnya pada April 1942 Hoegeng pulang kampung ke Pekalongan bersama karibnya, Totti Soebianto yang pulang ke Purwokerto. Mengisi waktunya bersama seorang teman, Soehardjo Soebroto, ia sempat berdagang kecil-kecilan, seperti telur dan buku-buku pelajaran Bahasa Jepang. Tak jarang, mereka berjualan sampai ke Pati dan Semarang (2009: 12). Soehardjo juga berkarir di kepolisian dengan pangkat terakhir brigjen.
Liku-liku Menjadi Polisi
KULIAH tak lanjut, ada hikmahnya juga bagi Hoegeng. Kantor Kepolisian Karesidenan Pekalongan membuka kursus polisi bagi pemuda pribumi berpendidikan minimal MULO. Waktu itu dibutuhkan polisi baru 11 orang, sesuai dengan jumlah perwira Polisi Belanda (termasuk yang Indo) yang sudah ditahan Jepang. Hoegeng mendaftarkan diri. Setelah seleksi, dari 130 pelamar ternyata ia merupakan satu di antara 11 yang diterima.
Saat itu, sebetulnya Hoegeng merasa agak keberatan. Karena, bukan untuk menjadi perwira polisi, sedangkan ia lulusan AMS yang sudah sempat menjadi mahasiswa hukum pula. Toh ia memutuskan jalani saja. Kursus Polisi Pekalongan (KKP) sepenuhnya diserahkan kepada orang-orang Indonesia yang dipimpin oleh Komisaris Polisi I R. Soemarto Soekardjo. Sumarto adalah Wakil Kepala Kepolisian Pekalongan, sedangkan kepalanya orang Jepang. Kelak di kemudian hari Soemarto menjadi Wakil Kepala Kepolisian Negara (KKN), sedangkan R.S. Soekanto KKN-nya (sekarang Kapolri, pen).
Semasa masih siswa KKP untuk jenjang hoofd agent polisi (kini dua tingkat di bawah Ipda) di Pekalongan, ia dan 10 temannya sudah menerima gaji bersih Rp11,50 setelah dipotong uang makan sebesar Rp19,50. Cukup menyenangkan untuk anak muda pada masa itu. Selain itu, mereka juga mendapat pembagian seragam, sepatu lars, handuk, topi pet, dan fasilitas lainnya.
Ada kebanggaan lain pada para siswa, mereka mendapat pembagian senjata api berikut amunisi dan dilatih menggunakannya. Di antara persenjataan itu, terdapat karaben peninggalan Belanda. Memiliki hak memegang senjata api, bagi Hoegeng sendiri penting, karena tidak sembarang orang dibenarkan menyimpan dan menggunakannya.
Di luar jam latihan, setelah pukul 14.00, mereka ditugaskan sebagai polisi reguler. Mengenakan seragam polisi, satu sama lain mendapat tugas beda-beda, seperti menjaga pintu pasar malam dan menangkap pelaku kejahatan. Ada pula yang bertugas menjaga kompleks pelacuran atau ditugaskan sampai ke lokasi-lokasi yang jauh di luar Pekalongan.
Setelah enam bulan menjalani kursus polisi, mereka diberi pangkat junsa bucho, setingkat di bawah hoofd agent II di zaman Belanda. Dalam kepangkatan Polri kini setingkat di bawah aipda (Santoso dkk., 2009: 15). Mereka kecewa, lantaran pangkat itu jauh di bawah harapan. Ketika mendaftar mereka menduga nanti setelah selesai pendidikan akan diberi pangkat Inspektur Polisi II. Di antara para alumni KKP yang terus berkarir di kepolisian, sempat mencapai kepangkatan perwira tinggi, antara lain Soedjono Partokoesoemo (Irjen Pol) dan Soerojo (Brigjen).
Setelah berjalan beberapa waktu, Hoegeng sempat terpikir untuk mundur saja dari polisi dan mencoba profesi lain, yaitu menjadi hakim. Pikirnya, hakim lebih enak, disiplin tidak seberat di polisi. Impiannya untuk menjadi polisi seperti sosok idolanya, Ating Natadikusumah, yang tinggi tampan selalu tampil gagah mengenakan seragam polisi, di pinggang selalu menggelantung sepucuk pisatol, dan kemana-mana bersepeda motor Harley Davidson, sempat goyah.
Selain sudah tak bersemangat lantaran kecewa, waktu itu seorang ahli hukum yang teman ayahnya, Mr. Besar Martokoesoemo mendorong Hoegeng, “Keluar sajalah (dari polisi, pen), biar saya uruskan sekolahmu biar jadi hakim.” Di kemudian hari, Hoegeng menikah dengan Mery, anak dr. Sumakno, mertua laki-laki Hoegeng yang tak lain adalah kakak dari Mr. Besar.
Di tengah kebimbangan Hoegeng, antara tetap jadi polisi atau keluar, datang pengumuman dari Pemerintah Pusat penajajah Jepang di Jakarta, bahwa telah dibuka pendidikan untuk Kader Polisi Tinggi (KPT) di Sukabumi. Sebenarnya, ia sendiri sudah kurang berminat, tetapi Soemarto mendaftarkan namanya untuk mengikuti tes masuk KPT. Ogah-ogahan ia jalani saja tes bersama 11 peserta lainnya yang juga alumni KKP. Para pengujinya terdiri atas tiga orang Jepang dan Soemarto sendiri. Kemudian, ia dinyatakan lulus bersama tujuh teman lainnya.
Seperti terlanjur, Hoegeng berangkat saja ke Sukabumi untuk menjalani pendidikan KPT di Sekolah Kepolisian Sukabumi. Di sini, Jepang menyelenggarakan dua tingkat pendidikan, yaitu Koto Kaisatsu Gakko (untuk tingkat KPT) dan Futsuka Kaisatsu Gakko (untuk Agen Polisi, AP). Tingkat KPT diperuntukkan bagi alumni kursus kepolisian, dengan peserta antara lain siswa asal Pekalongan, Purwokerto, dan Surabaya. Pendidikan tingkat AP diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari umum.
Selama pendidikan KPT, mereka digembleng oleh instruktur yang umumnya orang-orang Jepang. Mereka juga dilatih beladiri Jepang kendo, judo, dan jujitsu. Kenangan Hoegeng yang mendalam selama pendidikan, ia sering ditempeleng oleh instruktur Jepang, karena dianggap melanggar disiplin. Puluhan kali Hoegeng mengalaminya. Di antaranya ketika di sela-sela piket malam hari Hoegeng tertangkap tangan mencarikan nasi bungkus untuk tambahan makan malam sesama siswa yang tinggal di barak selagi tidak piket.
Memang, seperti diceritakan Hoegeng, pada malam hari mereka selalu kelaparan setelah seharian medapat latihan sangat berat, sementara makanan yang didapat terasa sangat kurang. Jadwal hari-hari pendidikan mereka, pukul 05.00 sampai 21.30. Padat diisi latihan, kecuali pada hari Kamis mereka bebas sehabis makan siang. Libur cuma hari Minggu, sampai pukul 18.00 (Santoso, 2009: 17).
Mendekati akhir pendidikan, muncul masalah terkait kepangkatan yang bakal mereka terima. Dari dua stel seragam warna abu-abu yang mereka terima, mereka sudah bisa mengetahui akan diberi pangkat bukan perwira, tapi minarai junsabucho. Pangkat ini selevel ini jauh di bawah inspektur polisi seperti yang dijanjikan ketika mulai masuk pendidikan KPT.
Gara-gara kepangkatan yang tak sesuai itu, mereka sempat frustrasi dan melakukan aksi mogok belajar. Pimpinan sekolah sampai-sampai meminta bantuan pimpinan bala Tentara Jepang Ke-16, Jenderal Harada, datang menenangkan siswa. Masalah ini cuma selesai sampai membuat pernyataan tertulis saja dari masing-masing siswa tentang protes berikut alasannya. Kemudian, Jepang hanya menyatakan senang karena siswa dianggap telah terbuka menyampaikan alasan melakukan protes.
Gegar Otak Ringan
SELESAI pendidikan KPT tahun 1944, ternyata benar Hoegeng dan kawan-kawan diberi pangkat minarai junsabucho. Sungguh menyakitkan. Tamat pendidikan KPT tapi ketika lulus diberi pangkat bintara. Kemudian, Hoegeng dan tiga rekannya, Soetrisno, Noto Darsono, Soenarto ditempatkan di Kantor Chiang Bu (Keamanan) Semarang.
Kantor Chiang Bu membawahkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Untuk kepolisian meliputi tiga bidang: Hoegeng dan Soenarto ditempatkan di Koto Kei Satsuta (DPKN, sekarang Intelkam), Noto di Keimu Ka (polisi umum), sedangkan Soetrisno di Keizai Ka (ekonomi). Kemudian Hoegeng menjadi Wakil Kepala Seksi II di Jomblang, Semarang.
Selanjutnya, ia naik menggantikan Kepala Seksi II, Koes Hadianto yang ditarik ke Bojong. Pada gilirannya, Hoegeng ditarik pula ke Bojong menjadi bawahan R. Soekarno Djojonegoro yang menjabat sebagai Keibu Ka Cho (Kepala Bagian Penjagaan). Di kemudian hari Soekarno menjadi KKN (1959 – 1964, kini Kapolri) menggantikan KKN pertama, R.S. Soekanto, yang diberhentikan BK menyusul permainan politik sejumlah bawahannya setelah ia membentuk Panitia Perencanaan Pelaksanaan Manifes Kepolisian (P3MK). Panitia ini, seperti ditulis Awaloedin dkk., bertugas membahas lima masalah pokok: status Kepolisian Negara, Kebijakan Keamanan, Retooling Dalam Lapangan Organisasi/ Kepolisian, Pendidikan, dan Pengawasan (2007: 296 – 301).
Membawahkan 60 personel, Hoegeng selaku Kepala Seksi II/ Penjagaan bertugas meliputi penjagaan pantai, lalu-lintas, penjagaan dan serangan udara. Suatu ketika Hoegeng bersama rekannya, Soenarto, ditugaskan Komandan Nipon Habara ke Tangeran, sebuah desa di selatan Salatiga. Tugasnya, melacak dan melaporkan apa yang disebut oleh Sidokang (orang Jepang yang menjadi atasan) sebagai pemuda-pemuda komunis. Padahal, sebenarnya mereka itu para pemuda dari Jakarta yang tengah menggalang perjuangan pemuda setempat.
Mengetahui hal itu, Hoegeng mengatur strategi dengan meminta agar Sidokang Tangeran saja yang membuat laporan. Alasannya, jika laporan yang ia buat isinya buruk, tentu akan tidak pantas bagi Sidokang Tangeran. Alasan ini diterima. Malah Sidokang setempat mengatakan, di Tangeran memang banyak serdadu Jepang yang nakal.
Benar saja, isi laporan yang dibuat Sidokang Tangeran berisi tentang kenakalan serdadu Jepang. Ketika laporan tersebut disampaikan, Sidokang Semarang dapat menerima dengan baik, meski ia sempat mempertanyakan mengapa isi laporannya bukan tentang pemuda komunis yang berkeliaran di Tangeran. Ketika itu Hoegeng dengan jujur menjelaskan, bahwa mereka tetap melakukan tugas, sedangkan laporan dibuat oleh Sidokang Tangeran. Laporan pun diterima dengan senang dan dinyatakan bagus.
Dalam pada itu, sejalan dengan pindah tugas, sejumlah penugasan, sampai menjadi Kepala Seksi II, Hoegeng mengalami kenaikan pangkat begitu cepat. Hal serupa juga dialami teman-temannya. Padahal, dalam kekecewaan mereka sudah tidak memikirkan lagi soal itu sejak frustrasi atas pangkat bintara yang diberi Jepang ketika selesai pendidikan perwira di KPT Sukabumi. Mereka mengira, mungkin ini cara Jepang berterima kasih dan minta maaf kepada Hoegeng dan kawan-kawan yang telah begitu berat menjalani pendidikan KPT Sukabumi.
Kenaikan pangkat yang dialami Hoegeng setelah bertugas di Semarang itu, dari Minarei Junsa Bucho menjadi Kei Bu Ho II atau Ajun Inspektur II. Kemudian naik menjadi Wakil Kepala Seksi II, pangkat dinaikkan pula menjadi Kei Bu Ho I atau Ajun Inspektur I. Selanjutnya, dinaikkan sekali lagi menjadi Kepala Seksi II di bawah Soekarno Djojonegoro. Gaji ikut naik pula. Dalam gurauannya, Hoegeng mengatakan, “Cuma dengan Jepang dalam dua tahun naik pangkat empat kali. Coba kalau Jepang lama berkuasa di Indonesia, mungkin cita-cita saya jadi Komisaris Polisi dapat dicapai lebih cepat” (Yusra dan Ramadhan, 1993: 107 – 108).
Jepang selama menjajah menitik-beratkan pendidikan yang bermuatan militer, termasuk dalam pendidikan polisi bagi orang-orang Indonesia. Potensi ekonomi, khususnya pertanian rakyat pun dikerahkan untuk kepentingan ekonomi perang. Semua dalam rangka mendukung Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya.
Memang, Jepang menjajah tak selama Belanda. Jelang penjajahan Jepang berakhir, beredar kabar-kabar di Tanah Air tentang Jepang kalah dalam perang menghadapi sekutu. Sementara perjuangan rakyat dan para pemuda yang sudah lama menghendaki Indonesia merdeka, tak pernah berhenti. Tanggal 14 Agustus 1945, sekutu membom Jepang di Hiroshima dan Nagasaki.
Pada perkembangannya, tga hari kemudian sampai juga di Semarang kabar, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta, pada 17 Agustus 1945. Seluruh polisi di Semarang dikumpulkan, termasuk para pemimpinnya seperti KBP I Salamun, KBP I Sumarsono, KP II Soegiri, IP I Soekarno Djojonegoro, IP I Soenarjo, dan IP II Hogeng sendiri, untuk mendapat penjelasan tentang kepastian kemerdekaan Indonesia.
Ternyata bukan dari pemerintah penjajah Jepang yang tampil memberi penjelasan, melainkan Soeprapto, teman ayah Hoegeng sewaktu ia Ketua Pengadilan (landraad) Karesidenan Pekalongan. Waktu itu, ayah Hoegeng, Soekario Kario Hatmodjo, seorang Kepala Kejaksaan di karesidenan yang sama. Di kemudian hari, Soeprapto menjadi Jaksa Agung yang banyak membongkar korupsi termasuk para pelakunya sejumlah Menteri. Begitu monumentalnya Soperapto karena tak mau kompromi dalam memberantas korupsi, sosoknya berupa patung kepala sebatas dada, kini dapat dijumpai di halaman Kejagung di Kebayoran, Jakarta Selatan.
Dalam briefing-nya, Soeprapto dengan santai menjelaskan, “Indonesia sudah merdeka. Kemarin sudah diproklamasikan di Jakarta…. Kita hanya patuh pada Pemerintah Indonesia. Kita orang Indonesia disuruh mengambilalih pemerintahan dari orang Jepang. Bagaiman caranya? Bilang saja pada pejabat-pejabat Jepang, ’Kamu pulang saja! Kita tak apa-apa sama orang Nippon’.” Menyusul briefing tersebut, seluruh lencana Hinomaru (bendera Jepang) mereka copot dari pet. Lalu, semua menggantinya dengan lencana merah-putih segi empat (Yusra dan Ramadhan, 1993: 123 – 124).
Bersamaan dengan kekalahan Jepang, bertebaran kabar-kabar di kalangan masyarakat, bahwa Belanda segera masuk membonceng sekutu untuk kembali menjajah. Padahal, Indonesia sudah merdeka. Di mana-mana, para pemuda bangkit merebut persenjataan Jepang. Tetapi, benarkah para pejuang damai-damai saja terhadap Jepang yang sudah kalah perang, seperti dianjurkan Soeprapto? Ternyata, para pemuda yang diamuk semangat merdeka tak hanya melakukan perampasan senjata Jepang, tetapi juga menganiaya. Di Semarang juga terjadi hal serupa.
Hoegeng mengingat-ingat, waktu itu 9 Oktober 1945 ia ditugaskan oleh Soekarno Djojonegoro ke Desa Candi. Ia mengendara sepeda motor dan mengalami kecelakaan. Mungkin akibat benturan saat terjatuh, kepala Hoegeng terasa sakit sekali, nyut-nyutan. Namun, dengan bantuan empat pemuda setempat, tugas mengevakuasi orang-orang Jepang yang menjadi korban tusukan bambu runcing, ke penjara Bulu, Semarang, dapat dilaksanakan.
Sebagian pemuda pejuang yang “mabuk kemerdekaan”, catat Hoegeng, tampaknya dijangkiti “superior complex”. Merasa sok kuasa, sok hebat sehingga bertindak overacting, bahkan sampai-sampai main tangan, bertindak brutal, menghina dan meludahi orang-orang Jepang. “Ini yang membuat orang-orang Jepang merasa terhina, lantas melawan atau berkelahi dengan pemuda Indonesia,” Hoegeng mengutip laporan Jepang (Yusra dan Ramadhan, 1993: 130)
Hoegeng yang merasa sakit di bagian kepala akibat terjatuh ketika bersepeda motor di kawasan Candi, esoknya memeriksakan diri ke dr. Soebijakto di RSU (CBZ) Semarang. Ia dinyatakan gegar otak ringan dan dokter menganjurkan rawat inap selama seminggu. Malam pertama di CBZ, ia ditempatkan satu ruangan dengan seorang pasien yang diinfus. Pasien ini sering mengerang dan mengingau saat tidur. Sungguh suatu pengalaman yang tidak nyaman.
Esoknya, Hoegeng diam-diam minggat dari CBZ. Agar tak diketahui oleh dr Soebjakto dan perawat, ia keluar melalui bagian belakang kompleks CBZ. Lucunya, malah lewat di depan rumah dr. Soebijakto dan bertemu dengan istri sang dokter yang rupanya tidak tahu dengan Hoegeng. Kepada Hoegeng, istri dr. Subijakto malah menyuruh sarapan pagi. Usai sarapan, Hoegeng langsung pulang ke rumah di Jalan Barusari 19, Semarang.
Minggatnya Hoegeng benar-benar rahasia di balik penyelamatan yang datang dari Tuhan. Dari Mas Petit Soeharto, Komandan Tentara Pelajar (TP) yang sengaja Hoegeng temui, diperoleh cerita, bahwa orang-orang Jepang marah lantaran para pemuda membunuhi orang-orang Jepang yang ditahan di Penjara Bulu. Dari Kidobutai Candi, orang-orang Jepang ramai-ramai ke Semarang mencari para pemuda, termasuk ke CBZ, tempat Hoegeng sempat dirawat semalam. Karyadi, dokter di rumah sakit tersebut terbunuh. Tak terbayangkan apa yang terjadi bila hari itu Hoegeng masih dirawat di CBZ. Entah bagaimana pula nasib pasien pengigau yang dirawat sekamar dengan Hoegeng.
Pada bagian lain, bentrok pemuda dengan Jepang telah menyulut “Pertempuran Lima Hari” di Semarang. Peristiwa ini berawal dari 14 Oktober 1945 ketika pemuda Indonesia mengangkut 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring ke Semarang. Para tawanan akan ditutup di Penjara Bulu, Semarang. Di perjalanan, sebagian tawanan melarikan diri meminta perlindungan ke Batalion Kido (Jepang). Kejadian ini menyulut kemarahan para pemuda, setiap orang Jepang yang ditemukan disergap dan ditawan. Kantor-kantor Pemerintah diduduki. Esoknya, tentara Jepang balas menyerbu. Pecahlah Perang Lima Hari di Semarang. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, diperikirakan mencapai 990 orang (Poespunegoro dan Notososanto,1993: 104).
Dimulainya pertempuran lima hari itu bertepatan dengan 25 tahun usia Hoegeng. Saat itu ia sedang sakit, divonis oleh dokter mengalami gegar otak ringan. Dalam susana kecamuk perang, malam-malam Hoegeng datang ke Kantor Pusat (Hoofd Bureaui) Kepolisan Semarang. Rupanya, di sana semua anggota polisi juga sudah berkumpul. Hoegeng yang tak sempat istirahat, merasakan sakit di kepalanya kian menjadi-jadi. Usai pertempuran, ia kembali ke CBZ dan oleh dokter tetap dianjurkan untuk istirahat.***