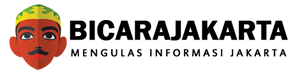6. IMAN SANTOSO HOEGENG
Oleh: Suryadi dan Helsi Dinafri
Suryadi, Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)/Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL). Helsi Dinafri, Praktisi Komunikasi.

BUKAN sekali saja Hoegeng berani “melawan” (dalam tanda petik) Bung Karno, Presiden I RI nan kharismatik. Jika terhadap Soeharto yang senantiasa tampil dingin dengan senyum yang sulit ditebak apa sesungguhnya di baliknya, Hoegeng benar-benar berani melawan, dengan BK ia pun berani berbuat “serupa”.
Waktu itu, ia baru menyelesaikan PTIK (1952). Nama lengkap Hoegeng yaitu Hoegeng Iman Santoso. Tetapi, ia terbiasa mencantumkan Hoegeng saja, seperti nametag pada seragam dinasnya. Selanjutnya duceritakan, ia dan teman-teman PTIK Angkatan I/ Parikesit (1952) berada di Istana Negara. Bung Karno (BK) ingin bertemu dengan bertemu dengan mereka.
Satu per satu mereka dipanggil maju untuk memperkenalkan diri kepada BK. Tiba giliran Hoegeng (-), BK (+) menanyakan siapa Namanya? “Hoegeng Pak,” jawabnya. Sejenak BK mengernyitkan dahi, kemudian terjadilah dialog hangat dan menggelikan:
(+) Lho, apa tidak salah. Biasanya kan Soegeng?
(-) Tidak Pak, itulah saya punya nama
(+) Tapi, ndak ada artinya itu. Itu bukan nama Jawa.
(-) Ndak tahu saya, saya dapat dari saya punya orangtua.
(+) Nah begini saja, Hem…apakah Hoegeng suka baca wayang, suka cerita wayang? (-) Ya suka, Pak.
(+) Nama yang baik seperti nama saya, Sukarno begitu. Kan nama wayang itu. Nah,
begini saja, mbok ya nama jij (kamu, Belanda – Indonesia, 1996: 213) itu diganti saja.
(-) Diganti bagaimana Pak?
(+) Diganti Sukarno begitu
(-) Oh nggak bisa, Pak!
(+) Lho, kok nggak bisa?
(-) Ya, nama Hoegeng itu saya dapat dari saya punya orangtua. Kalau saya berganti nama Sukarno pula, sedangkan pembantu rumahtangga saya namanya Sukarno juga, wah…
(+) kurang ajar kamu
(-) Ah tidak Pak
(+) Benar-benar kurang ajar kamu! (tetapi, saat itu wajah BK tampak cerah)
Kalimat “sedangkan pembantu rumahtangga saya namanya Sukarno,” yang disampaikan Hoegeng bukan untuk merendahkan BK. Tetapi, saat itu ia seperti terdesak di satu sisi oleh sikap kebapaan BK, dan di lain sisi oleh orangtua yang telah memberinya nama Hoegeng. Maka, spontan saja kalimat itu terucapkan.
“Dalam batok kepala saya membersit ‘akal’ atau gaya Pekalongan,” ungkap Hoegeng yang lalu nyerocos seenak dengkulnya seperti itu (Yusra dan Ramadhan, 1993: 20 – 21). Itulah Hoegeng dengan gaya Pekalongan, sementara BK yang punya darah Jawa Timur, seperti halnya Mas Ban juga pernah hidup dan bersekolah di Surabaya.
Begitulah kejadian tersebut. Tak ada dampak selanjutnya pada kepangkatan dan karir kepolisian Hoegeng karena “melawan” Presiden. Bahkan, di kemudian hari, Hoegeng diangkat oleh BK menjadi Menteri Iuran Negara. Saat pertama kali menjadi menteri itu pula, ia di kantornya mendapat perlakuan gaya Pekalongan dari sahabat kecil sepermainannya, Hasan, seperti telah diungkap dalam bagian tulisan ini sebelumnya.
*Lukisan atau “Korupsi Terselubung”?*
BAHWA Hoegeng tak meninggikan dan merendahkan orang dalam bergaul, itu fakta. Bahkan, meski menyandang jabatan tinggi, ia tak segan-segan mengakui secara konkret bahwa seorang bawahan itu benar bila memang benar.
Ini ceritanya tentang Hoegeng dan seorang bawahannya. Waktu itu Hoegeng (+) masih Kepala Djawatan Imigrasi (JI). Melalui surat tulisan tangan dengan “tinta merah”, ia memanggil Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Medan, Sumut, Saleh Wiramihardja (-). Rupanya, ia murka setelah mendengar kabar sepihak yang tak tuntas, atau boleh jadi cuma fitnah.
Dalam buku “Di Bawah Naungan Sumpah Jabatan” (“DBNSJ”), terungkap Saleh menghadap Hoegeng di Kantor Jawatan Imigrasi di Jakarta. Begini dialog antara Hoegeng dan Saleh (Wiramihardja, 2006: 66 – 68):
(+) Apakah tidak tahu ada instruksi Kepala Jawatan Imigrasi tentang larangan berdagang (bisnis) dengan pedagang “WNI” (dalam tanda petik, pen)?
(-) Ya, tapi ini demi menjaga disiplin kerja para pegawai.
(+) Kenapa U tidak minta berhenti saja dari Jawatan Imigrasi atas dasar melanggar larangan saya sebagai atasan U? (kata U tanda ia tak menstratakan siapa pun di hadapannya. Dala Bahasa Belanda U diartikan: menyebut orang kedua secara umum tidak membedakan pangkat kedudukan, seperti Anda dan saudara/Belanda – Indonesia, 1996: 525).
(-) Saya tidak akan keluar dari Jawatan Imigrasi, karena saya tidak merasa berbuat suatu kesalahan atau pelanggaran atas apa yang telah saya lakukan, karena saya tidak ada maksud menguntungkan diri saya pribadi. Tapi, kalau Pak Hoegeng menetapkan saya telah melakukan kesalaha atau pelanggaran silakan Bapak pecat saya dari kedudukan saya sebagai Pegawai Negeri dan tentu saya akan keluar dari Jawatan Imigrasi. Tapi, di lain pihak Bapak hendaknya mendengar pendapat saya tentang diri Bapak. Begitu banyak ‘pengusaha keturunan’ di Medan yang di rumah- rumahnya memiliki lukisan yang dilukis oleh Bapak selagi Bapak menjadi Kepala Polisi Medan. Mereka itu tidak mengerti seni, tapi kepada setiap tamu yang diundang ke rumahnya akan dia perlihatkan llukisan yang Pak Hoegeng lukis itu untuk menyatakan dengan nada bangga, bahwa dia kenal pribadi dengan Pak Hoegeng selaku Kepala Polisi di Medan dan berarti alat negara yang akan menindak dia harus berhati-hati. Is dat dan geen corruptive, Pak (apakah itu bukan korupsi terselubung, Pak?)”.
Sejenak Hoegeng tersentak dan betul-betul terdiam. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba ia memeluk Saleh Wiramihardja, laki-laki di hadapannya itu, dan berkata: “Het is eem misverstand tusen on, Mas! Gaat gau terug naar uw standplast (ini adalah suatu kesalahpahaman antara kita, Mas! Segeralah kembali ke tempat kedudukan).
Akan tetapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Saleh menjadi Kakanim di Medan selama delapan tahun. Sebelum menjadi Kepala JI, Hoegeng di Medan menjabat Kepala Bagian Reserse Kriminal Kodak Sumut. Waktu itu, Medan sangat terkenal karena kegiatan illegalnya, seperti “smokkel” (Belanda – Indonesia, 1996: 458) dan perjudian. Para pelakunya banyak dari kalangan pebisnis “WNI” keturunan.
Hoegeng tak pernah mau kompromi dengan kejahatan apa pun yang terjadi di wilayah tugasnya, termasuk penyelundupan dan perjudian. Prinsipnya apa pun tindakan ilegal harus diberantas tanpa pandang bulu siapa pelakunya. “Saya tahu dari para perwira Polri eks anak buah Pak Hoegeng bahwa beliau paling tidak suka kalau anak buahnya berbisnis dengan pedagang “WNI” (dalam tanda petik),” ungkap Saleh.
Pada masa itu, untuk kebutuhan pangan, pegawai negeri sangat bergantung beras jatah dari pusat yang dibagikan oleh Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN). Suatu ketika beras terlambat datang dari pusat selama beberapa bulan. Pegawai sudah tampak gelisah. Untuk mengatasinya, Saleh menghubungi grosir di Pasar Pajak Medan yang biasa menyuplai beras ke semua LP dan Perkebunan Negara di Sumut. Saleh berhasil meminjam beras dari grosir itu sebanyak jatah kantor melalui PKPN.
Kepada grosir itu, ia berjanji apabila terjadi perbedaan kualitas dengan beras jatah dari pusat, ia bersedia mengganti perbedaan harganya. Grosir itu memang benar sudah ia kenal sebelumnya. Momennya beberapa waktu lalu ketika ia menolong anak sulung si grosir saat menjalani perawatan di RSJ Bogor, Jabar.
Saleh, putra pasangan guru kelahiran Tasikmalaya, Jabar, 28 Oktober 1929 (persis setahun setelah ‘Soempah Pemoeda’ di Jakarta). Ia menjadi Kakanim di Medan, 1961 – 1968. Dirjen Imigrasi M. Iman Santoso (bukan Hoegeng) dalam pengantar buku “DBNSJ” (26 Januari 2006) menulis, “…Saleh Wiramihardja memang sosok legendaris di lingkungan Imigrasi. Di manapun ditugaskan beliau dikenal sebagai pejabat jujur yang suka menolong namun selalu teguh dalam prinsip” (Wiramihardja, 2006: v).
Saat memimpin JI, Hoegeng adalah seorang polisi aktif. Ia tak pernah melepas baju dinas polisinya. Gaji tetap diperoleh dari Kepolisian. Dari Imigrasi ia tak mengambil apa-apa termasuk fasilitas sebagai Kepala JI. Ia mulai memimpin JI tanggal 19 Januari 1961, menggantikan Notohatyanto (imigrasi.go.id). Ia mengemban tugas sebagai Kepala JI sampai Juni 1965, sebelum dipromosikan menjadi Menteri Iuran Negara. Hoegeng digantikan oleh wakilnya, Widigso Sudigman.
Widigdo sebelum menjadi Wakil Hoegeng memang orang Imigrasi yang ditugaskan menjadi Konsul RI di Hongkong. Ia dipanggil pulang untuk menjadi Wakil Kepala JI atas permintaan Hoegeng kepada Menko Hankam, Jenderal A.H. Nasution. Hoegeng saat itu memerlukan orang Imigrasi yang berpengalaman dan berwawasan luas tentang keimigrasian, untuk pembenahan di JI. Terbukti, sejak itu perlahan-lahan dapat dilakukan pembenahan dan pemantapan di dalam JI. (Yusra dan Ramadhan K.H., 1993: 251 – 256).
Pada masa itu situasi dan prosedur kerja di JI berjalan semrawut. Jauh dari mandiri. Hoegeng menggambarkan: “…. Kantor Imigrasi dewasa itu tampaknya tidaklah dikuasai oleh orang Imigrasi. Yang berkuasa justru orang non-Imigrasi, seperti dari bagian Intel Angkatan Darat, atau DPKN Kepolisian, atau CPM, atau kejaksaan Agung. Jawatan Imigrasi hanya berfungsi sebagai jurutulis dan tukang setempel saja”.
Menurut Hoegeng, “Secara sederhana dapat saya katakan, Jawatan Imigrasi merupakan unsur Departemen Kehakiman, namun dalam hal yang menyangkut security nasional di bawah Hankam. Menko Hankam sendiri adalah Komandan Tertinggi Operasional dan Teknis Imigrasi (Yusra dan Ramadhan, 1993: 249 – 251).
Dapat dibayangkan macam apa semrawutnya JI pada masa itu. Wajar jika dituduhkan bahwa yang membuat semrawut tata kelola JI, adalah intervensi-intervensi kekuasan dari luar JI. Sementara di JI sendiri banyak orangnya yang “menikmati permainan” terkait urusan keluar-masuk antarnegara, baik bagi WNI maupun orang asing, pengusaha atau diplomatnya. Wajar saja jika Hoegeng sampai mengatakan, Jawatan Imigrasi cuma jurutulis dan tukang setempel.
Suasana semrawut JI semacam itu, agaknya, membuat Hoegeng kian tegas menegakkan disiplin dan aturan. Tak ada kompromi. Kehormatan senantiasa hendaklah dipelihara. Ini ajaran penting yang selalu dipesankan oleh Sang Ayah, Sukario Kario Hatmodjo, seorang amtenar di Pekalongan.
Di masa-masa pertumbuhan Hoegeng di Pekalongangan, ayahnya adalah seorang Kepala Kajaksaan Karesidenan. Ia tak punya rumah sendiri. Dari waktu ke waktu keluarga priyayi ini tinggal menempati rumah kontrakan; Sejak masih amtenar di masa penjajahan, setelah merdeka, hingga meninggal dunia. Sejarawan Prof. Asvi Warman Adam menulis, “…pendirian yang ditanamkan oleh ayahnya, bahwa yang penting dalam kehidupan manusia adalah kehormatan. Jangan merusak nama baik dengan perbuatan yang mencemarkan” (Santoso, 2009: ix).**