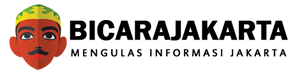Jakarta, Bijak
Suryadi, M.Si
Pemerhati Budaya dan Kepolisian
Tindakan penghentian penyidikan terhadap Murtede (M), yang awalnya disangka telah menghilangkan nyawa dua pembegal, sudah tepat. Tetapi, adalah penting masyarakat memahami bahwa tindakan polisi itu, bukan
sekadar keberpihakan pada emosional massa.
Hal serupa bisa saja terjadi di tempat lain di tanah air.
Masih hangatnya “kasus M” adalah momen bagus bagi Polisi mengagendakan pendalaman kepada internal polisi dan eksternal masyarakat dalam rangka membangun pemahaman, bahwa “mencegah
jauh lebih baik ketimbang suatu kejahatan
terlanjur terjadi”, dan pentingnya menghindar
dari “main hakim sendiri”.
SEPERTI pemberitaan media, M (34) dan isteri, Mariana (32) bersama dua anak mereka, adalah warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), NTB. Pada Minggu malam (10/4/22) M bepergian mengendarai sepeda motor, dengan tujuan menjenguk Ibunya di Lombok Timur (Lotim).
Masih di jalan Desa Ganti, M dipepet oleh empat laki-laki yang berboncengan dengan dua sepeda motor. Mereka yang ternyata pembegal ini, dengan menggunakan senjata tajam clurit, secara paksa berusaha merampas sepeda motornya M.
Dengan sebilah pisau di tangan, M dalam “keadaan terpaksa” membela diri melakukan perlawanan dan berhasil. Dua dari emat pembegal (OWP dan PE) dibuatnya terkapar berlumuran darah, tewas. Dua pembegal lainnya, HO dan WA, yang juga luka-luka kabur. Kronik selanjutnya:
• M menenangkan diri di rumah keluarganya.
• Polres Loteng dari tempat kejadian (TKP) mengamankan barang bukti empat senjata tajam, tiga unit sepeda motor (satu milik M dan dua lainnya milik pembegal).
• Kamis, 15 April 2002, Kapolsek Praya Timur, Iptu Sayum mengatakan, “Kemarin (Rabu, 14/4/22), OWP dan PE telah dikuburkan di TPU Desa Beleka.”
• Polres Loteng memintai keterangan korban begal, M alias AS.
• Selain menetapkan HO dan WA sebagai tersangka, Polres Loteng juga menyidik M sebagai tersangka dan menahannya. Dalam konferensi pers, Wakapolres Kompol I Ketut Tamiana menjelaskan, “AS dikenakan Pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang, melanggar hukum. Pasal 351 KUHP ayat (3) (berbunyi) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang.”
• Masyarakat yang pro pada tindakan M meminta agar M segera dibebaskan. Alasannya, ia korban yang membela diri.
• Di lain pihak, keluarga HO dan WA yang belum tahu persoalan sesungguhnya, meminta agar Polisi mengungkap latar belakang meninggalnya HO dan Wa.
• Polda mengambil alih penanganan kasus M, kemudian mengadakan gelar perkara dengan menghadirkan pakar hukum. Dasarnya, Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan, tepatnya Pasal 30 menyatakan, “Penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.”
• Sabtu, 16 April 2022, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Irjen Pol. Djoko Purwanto lewat keterangan tertulis menyatakan: “Gelar perkara menyimpulkan, peristiwa (AS) itu merupakan perbuatan ‘pembelaan terpaksa’ sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil. Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh AS mengakibatkan dua dari empat pembegal tewas. Tindakan ini merupakan pembelaan diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang ‘pembelaan terpaksa’. Kemudian, Polisi menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3)”.
• Di Jakarta Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan, “Penghentian perkara tersebut, dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas.”
• Sebelum itu, di hari yang sama, Sabtu, 16 April 2022, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta: “Proses hukum atas kasus korban begal jadi tersangka di NTB segera dihentikan.”
Pemahaman
POLISI telah menghentikan penyidikan atas M setelah didahului gelar perkara yang menghadirkan pakar hukum. Langkah polisi ini, seperti dikemukakan Kapolda NTB, didasarkan atas Pasal 30 Perkap 6 Tahun 2019. Selain itu juga juga sudah bersesuaian dengan Pasal 49 (1) KUHP yang selengkapnya berbunyi:
“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan,
karena ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun
orang lain, tidak dipidana.”
Hemat penulis, sejalan dengan alasan formal yang melatarbelakangi penghentian penyidikan M tadi, Polisi masih punya kewajiban memperdalam pemahaman yang lebih baik di internal polisi sendiri dan masyarakat di eksternal. Sebab, hal serupa bisa saja terjadi lagi di daerah lain di tanah air.
Untuk itu diperlukan bukan cuma penyuluhan atau sosialisasi yang berbau formalistik searah datang dari penegak hukum dan ahli hukum, yang hanya menjadikan masyarakat sebagai pendengar. Agenda ini, hendaknya berlangsung dialogis, diisi oleh perpaduan praktis antara sosialisasi dan simulasi mendekati kenyataan praktis.
Bahasa-bahasa hukum dalam kalimat yang mudah dipahami secara praktis, dalam hal tersebut, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan paham secara baik. Misalnya, ketika ditegaskan, bahwa Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas. Selain itu, juga ”pembelaan terpaksa” yang dimaksudkan dalam KUHP, dan apa yang dimaksudkan, “Penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.”
Kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut cuma contoh-contoh yang perlu disederhanakan ke dalam pemahaman praktis masyarakat, tanpa meninggalkan hal ideal dan filosofisnya. Apalagi, di tengah amuk emosi, terbatas, dan bervariasinya pemahaman teoritis, patut diduga masyarakat akan menerima begitu saja penjelasan yang cenderung formalistik searah, asalkan keinginan seketika mereka terpenuhi. Dalam konteks kasus serupa M, keinginan kolektif seketika massa adalah “bebaskan”.
Jadi, mengingat potensi gangguan keamanan dan ketertiban bersumber dari kerawanan, baik secara ideologi, politik, ekonomi, maupun budaya (ipoleksosbud) ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka yang patut menjadi titik perhatian utama adalah tercapainya pemahaman yang baik dari masyarakat itu sendiri.
Masyarakat yang dimaksudkan adalah, “Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama” (KBBI, 2002: 731). Artinya, Polri yang sudah memiliki ilmu “kebinmasan” dituntut arif, mampu, dan mau bekerja lebih merangkul berbagai potensi masyarakat agar kesertaan mereka betul-betul merepresentasikan signifikansi bagi makna adil dalam penegakkan hukum.
Dari situ diharapkan pula, masyarakat akan dewasa (matang pikiran dan pandangan”, KBBI, 2002: 260) dalam memahami tindakan-tindakan yang diambil sepanjang proses yang didasarkan pada hukum. Penting dimengerti pula, ciri dewasa adalah mandiri sehingga terhindar dari gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang menjauh dari akal sehat dan kejujuran hati nurani. Ini tidak hanya penting ada pada masyarakat, tetapi juga pada polisi sendiri.
Main Hakim Sendiri
PENDEK kata, Polri sepanjang tugas hukum kesipilannya, masih akan terus disibukkan oleh sejumlah agenda membawa masyarakat dan dirinya sendiri, untuk membingkai diri dalam penegakkan hukum demi kamtib yang kondusif bagi kehidupan masyarakat. Hal semacam ini, misalnya, akan gampang terlihat bila masyarakat sudah tidak lagi mudah terpanggang oleh frasa-frasa provokatif bahwa “penegak hukum tidak adil”.
Hal serupa itu, harus diakui, sempat meronai pemahaman masyarakat ketika proses hukum berjalan atas M. Bukankah, sebelumnya sampai pada keputusan penghentian penyidikan, di masyarakat muncul teka-teki polisi akan “melanjutkan penyidikan” atau sebaliknya “menghentikannya”.
Sejalan dengan pemahaman sementara seperti dalam kasus M, bahwa “M adalah korban begal yang ditersangkakan”, patut dihilangkan imej masyarakat bahwa tindakan serupa M adalah benar hanya lantaran yang dibunuhnya pelaku kriminal, begal.
Jika hal tersebut tidak segera dicarikan solusinya, bukan mustahil pemahaman seperti itu akan berlanjut menyulut masyarakat menjadi emosional. Kemudian, membabi-buta dan berujung pada tindakan “main hakim sendiri”. Dalam peristiwa serupa ini, kerap pelaku kriminal babak-belur setengah mati. Tetapi, ada pula yang meninggal sebelum sempat diberikan pertolongan. Padahal, yang membedakan pelaku kriminal dengan bukan pelaku kriminal, sudah sangat jelas. Tetapi, akibat “main hakim sendiri”, si pengeroyok berubah menjadi pelaku penganiayaan, bahkan pembunuh.
Bukankah secara empirik, misalnya, masih sering terdengar ada amuk massa terhadap copet, pencuri jemuran di siang hari, maling alas kaki, kotak amal, atau alat pengeras suara rumah ibadah? Permaafan bagi pencuri seperti ini, serupa dengan yang diberlakukan terhadap penganiaya, yaitu: Proses hukum!
Tidak mudah, memang, bagi penegak hukum untuk membawa dirinya sendiri bersama masyarakat, utuk bersama-sama masuk ke dalam rasionalitas berhati. Terlebih ketika berhadapan dengan tindak kriminal yang berpangkal pada emosi massa.
Akan tetapi, bagaimanapun, “mencegah jauh lebih baik ketimbang kejahatan terlanjur terjadi”. Sebab, emosional kolektif massa bukan cuma desakan agar orang-orang seperti M alias AS dibebaskan, melainkan ada pula yang menyulut dan tersulut untuk mengambil tindakan “main hakim sendiri”. Sungguh, jelas ini kerja keras. Tuntutannya, kerja cerdas yang berujung pada tegas namun tetap humanis!***